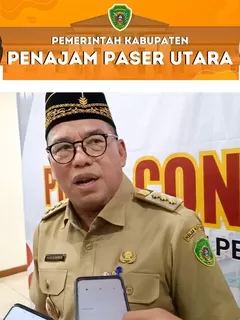Ferdy Sukmadianto
ASN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim
Kinerja keuangan daerah merupakan indikator dan tolok ukur sejauh mana daerah telah menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola keuangannya. Kinerja keuangan daerah biasanya dilihat dari capaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD secara periodik (tahunan) diperiksa dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui tingkat kewajaran, relevansi serta kecukupan materialitas yang diungkapkan dalam penyajian laporan keuangan tersebut.
Hasil pemeriksaan oleh BPK berupa opini audit yang disusun melalui serangkaian prosedur dan analisis terhadap prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang terstandardisasi dan diterapkan oleh pemerintah daerah. Hasil opini audit BPK secara linear dipandang sebagai hasil akhir capaian LKPD, namun demikian penggunaan informasi LKPD sendiri secara komprehensif bertujuan memberikan arah kebijakan pembangunan daerah oleh pimpinan daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang optimal.
Dari beberapa pengamatan, tidak banyak dan hanya sedikit pimpinan daerah yang mengerti dan memahami informasi dari LKPD untuk digunakan sebagai bahan kebijakan penyusunan strategi pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Banyak pimpinan daerah yang menganggap urusan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan anggaran daerah. Semakin banyak anggaran daerah maka urusan peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin tinggi begitupun sebaliknya, hal ini merujuk kondisi ruang fiskal daerah. Anggapan tersebut tidak seluruhnya salah namun juga tidak bisa dibenarkan seratus persen.
Mengapa demikian, kalau berpedoman pada tujuan pemerintah dan tujuan bernegara orientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama pembangunan. Ini menandakan bahwa urusan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak bisa ditawar lagi. Cukup atau tidak cukupnya anggaran daerah untuk kesejahteraan masyarakat bukan suatu alasan urusan kesejahteraan diabaikan.
Kondisi anak putus sekolah, tingkat kesehatan bayi, angka harapan hidup, tingkat pendapatan per kapita regional serta ukuran-ukuran kesejahteraan lainnya dalam statistik makroekonomi menjadi problem aktual penyelenggaraan kepemerintahan di daerah. Akumulasi tidak tertanganinya permasalahan kesejahteraan tersebut akan menjadi beban pemerintah pusat di sepanjang waktu dan ini menjadi permasalahan klasik di setiap pemerintah berbagai negara berkembang di dunia.
Apabila pertanyaan dikembalikan lagi kepada peran pemerintah daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah serta pilihan kebijakan apa yang terbaik agar kualitas kesejahteraan masyarakat selalu meningkat maka yang akan muncul adalah berbagai argumen dan narasi yang justru semakin melebar ke sana kemari dengan dibumbui sentimen politik yang melatarbelakanginya.
Untuk dapat memilah bagaimana kualitas kesejahteraan masyarakat di suatu daerah diukur selain dengan data makroekonomi yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS), pimpinan daerah dapat memanfaatkan informasi dari LKPD yang dihasilkan sebagai alat analisis dasar bagaimana kinerja keuangan daerah berdampak kepada program pembangunan yang bertujuan menciptakan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.
Ukuran umum tingkat kesejahteraan masyarakat yang sering digunakan adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Berdasarkan data yang diolah di Provinsi Kaltim, kurun waktu 2016 – 2020 tren rata-rata IPM di tingkat pemerintah kabupaten/kota 73,82 dengan nilai IPM tertinggi di Kota Samarinda 79,92 dan terendah di Kabupaten Mahakam Ulu 66,59 sementara trend kenaikan IPM di Kota Samarinda 1,5 persen dan Kabupaten Mahakam Ulu 2,3 persen. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja di LKPD dalam kurun waktu yang sama terjadi perbedaan yang signifikan dimana tren kenaikan anggaran belanja di Kota Samarinda mencapai 24,52 persen dan di Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 31,83 persen.
Kondisi ini menunjukkan kenaikan realisasi belanja sebanding dengan kenaikan IPM namun derajat kenaikannya tidak signifikan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan belanja pemerintah daerah belum sepenuhnya memacu kenaikan derajat kesejahteraan secara tinggi.
Terdapat contoh aktual dalam strategi kebijakan publik yang diawali dari analisis laporan keuangan pemerintah. Strategi kebijakan publik yang kemudian populer tersebut yakni saat Presiden Amerika Serikat, Barack Obama meluncurkan Undang Undang Perlindungan Kesehatan yang dikenal dengan Obama Care pada tahun 2010. Banyak pihak yang menyinggung program Obama Care sebagai program mercusuar Presiden Obama agar citra dirinya meningkat di mata masyarakat AS saat itu.