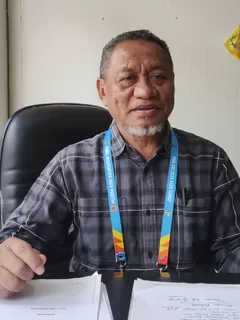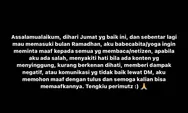ARTIS Marcell Darwin, 29, bakal melepas masa lajang. Bintang sinetron dan pemain film itu akan menikah dengan Nabila Faisal yang dikencaninya sejak Juli 2019. Marcell dan Nabila sudah mendaftarkan pernikahan ke KUA Kebayoran Baru. ’’Iya, bener. Tanggal 12 (Januari) nanti gue menikah,’’ kata Marcell kemarin sore (7/1) di launching poster dan trailer film Nikah yuk!.
Pernikahan tersebut bakal dilangsungkan di Jakarta. Keduanya hanya mengundang keluarga dan kerabat. ’’Nggak pakai adat apa-apa. Modern dan simpel aja,’’ tutur mantan pacar Cinta Laura itu. Terkait kabar perbedaan keyakinan antara dirinya dan Nabila, Marcell enggan membenarkan maupun menyanggah. ’’Kata siapa beda (keyakinan)? Menurut kalian beda, tapi menurut gue sih nggak beda,’’ ujar cowok blasteran Makassar-Jerman tersebut.
Marcell juga enggan mengungkapkan prosesi keagamaan dari pernikahannya dengan Nabila. Apakah pemberkatan nikah atau akad. ’’Mohon doanya aja supaya lancar pas hari H,’’ ucapnya. (len/c18/jan)